Penulis: Irma Syuryani Harahap
Editor: Ryo Disastro
Setelah mengikuti diskusi daring bersama Prof. Yudhie Haryono dan Kirdi Putra—dalam forum tematik mingguan bertajuk “Banjir Sumatera Belum Jadi Bencana Nasional”—satu kesadaran menghantam lebih keras dari suara hujan: apa yang terjadi di Sumatera bukan sekadar musibah alam. Ia adalah luka panjang yang dirancang, dipelihara, dan dilegalkan.

Bencana alam di Sumatera
Mari duduk merapat. Pegang tanganku sejenak. Jangan lepaskan dulu. Dengarkan luahan ini—bukan sekadar keluh, tetapi jerit nurani. Biarlah tulisan ini menjadi tancapan demi tancapan kecil ke kesadaran mereka yang terlalu lama memuja pertumbuhan, tetapi lupa pada keberlanjutan. Agar martabat kemanusiaan kembali menemukan jalannya.
Sejarah Sumatera sesungguhnya memberi peringatan dini. Pada masa kolonial, Belanda membagi wilayah hutan Nusantara ke dalam kategori hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan konservasi. Peneliti BRIN mencatat, Sumatera sejak awal dinilai tidak cocok untuk ekspansi perkebunan monokultur seperti sawit karena kondisi tanahnya yang rapuh dan curah hujan yang tinggi. Fokus kolonial kala itu adalah karet, kopi, dan tembakau. Sawit hanya hadir secara terbatas di awal abad ke-20, bukan sebagai prioritas.
Ironisnya, justru setelah Indonesia merdeka, kebijakan berubah drastis. Sejak dekade 1970-an, kawasan yang dulu ditetapkan sebagai hutan lindung mulai dikonversi menjadi perkebunan sawit dan wilayah tambang, terutama di Riau dan Sumatera Utara. Sumatera yang dahulu dijaga sebagai penyangga ekologis perlahan diubah menjadi ladang eksploitasi.
Hari ini, penguasaan perkebunan sawit di Sumatera sangat terkonsentrasi. Data menunjukkan total luas sawit di Sumatera mencapai sekitar 8,78 juta hektare, hampir separuh dari total nasional. Provinsi dengan sebaran terluas adalah Riau, disusul Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan Aceh.
Nama-nama besar yang mendominasi: Wilmar International, Sinar Mas Group (Golden Agri-Resources), Royal Golden Eagle (RGE/Asian Agri), Musim Mas, Astra Agro Lestari, serta PTPN Group, khususnya PTPN IV dan PTPN VII. Di luar itu memang ada perkebunan rakyat (plasma), tetapi skala penguasaan lahan tetap berada di tangan segelintir konglomerat.

Kebun sawit yang marak dan diduga kuat berdampak negatif terhadap lingkungan dan berkontribusi pada bencana di Sumatera.
Konsentrasi kepemilikan ini menimbulkan dampak serius. WALHI mencatat bahwa antara 2016–2025, sekitar 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hilang akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PLTA, dan proyek ekstraktif lainnya. Global Forest Watch bahkan mencatat sekitar 11 juta hektare hutan primer basah Indonesia hilang dalam periode 2002–2024, dengan Sumatera sebagai salah satu episentrum terparah.
Akibatnya kini kita saksikan bersama. BNPB mencatat lebih dari 900 orang meninggal dunia, ratusan lainnya hilang, dan 800 ribu hingga 1,1 juta warga terpaksa mengungsi akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga akhir 2025. Ribuan rumah, jembatan, dan fasilitas publik hancur. Kerugian ekonomi membengkak, sementara PPATK memperkirakan shadow economy Indonesia mencapai 30–40 persen PDB, sebagian terkait aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan pencucian kayu.
Inilah yang membuat bencana di Sumatera layak disebut by design. Bukan dalam arti konspirasi gelap yang mistis, tetapi dalam bentuk desain kebijakan: izin yang diterbitkan, hutan yang dilepas, tambang yang dilegalkan, dan ruang hidup masyarakat yang dikorbankan. WALHI menyebutnya sebagai “legalisasi bencana ekologis”, sementara NU Online menegaskan bahwa ini adalah bentuk perampasan ruang hidup demi kepentingan ekonomi elit.
Lebih menyakitkan lagi, bencana sering dijadikan panggung politik. Elit datang membawa bantuan darurat, berfoto, lalu pergi—tanpa perubahan kebijakan struktural. Alam dibiarkan menanggung luka yang sama, berulang kali.
Padahal faktanya jelas: pemilik utama perkebunan sawit di Sumatera adalah konglomerat besar dan BUMN, bukan masyarakat adat atau petani kecil. Riau dan Sumatera Utara menjadi pusat ekspansi. Dampak sosial dan ekologisnya tak terelakkan: konflik agraria, ketimpangan akses tanah, rusaknya ekosistem, dan hilangnya masa depan generasi berikutnya.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Prof. Yudhie memberi jawaban yang sederhana namun fundamental: mulai dari state of mind. Menulis. Menyebarkan kesadaran. Menjadikan gagasan sebagai virus yang wangi—bergerak dari pikiran ke publik, dari publik ke kesadaran kolektif, hingga menekan kursi-kursi kekuasaan agar kembali berpijak pada kewarasan.
Gotong royong bukan nostalgia. Ia adalah jalan pulang. Agar Sumatera tidak terus menangis sebagai banjir, tetapi kembali bernapas sebagai hutan. Agar pembangunan tidak lagi menjadi alasan untuk merusak, dan agar martabat manusia kembali berdiri sejajar dengan alam yang menghidupinya.(*)
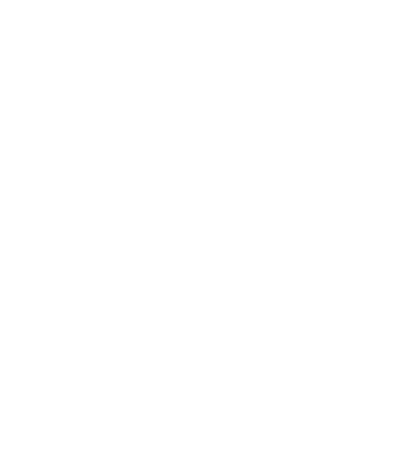
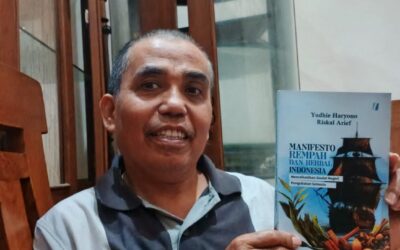

0 Comments